Perkenalan saya dengan tokoh tragis ini tidak berlangsung secara linear. Ia datang melalui serangkaian kebetulan kecil yang saling berkelindan, hingga pada suatu hari menuntun saya benar-benar menapakkan kaki di Rangkasbitung.
Berawal dari Sebuah Catatan Pinggir
Ia bermula bukan dari buku Max Havelaar itu sendiri, melainkan dari fragmen-fragmen pemikiran tajam Goenawan Mohamad dalam buku Catatan Pinggir. Di sana, Saija tidak lagi sekadar tokoh fiksi dari abad ke-19. Ia menjelma sebagai wajah sunyi dari ketidakadilan yang sistemik, korban dari kekuasaan yang bekerja tanpa nurani.
Saya teringat satu kutipan Multatuli yang dikutip Goenawan Mohamad:
“Tapi jika ada orang di antara kita yang melalaikan kewajibannya, atau yang merampas kerbau dari orang miskin, siapa yang akan menghukumnya?”
Di situlah pangkal tragedi Saija dan Adinda bermula. Bukan dari cinta yang terlarang, melainkan dari kemiskinan yang dipaksakan melalui perampasan. Kerbau-kerbau milik ayah Saija direnggut oleh penguasa lokal yang korup, menjadikan hidup mereka terhenti sebelum sempat dimulai.
Saija, pemuda dari Desa Badur, terpaksa meninggalkan Adinda demi sebuah harapan yang getir. Ia merantau ke Batavia selama 36 bulan dengan satu tujuan sederhana: mengumpulkan cukup perak untuk membeli seekor kerbau, syarat agar ia dapat menikahi Adinda dan menyambung hidup. Mereka berjanji akan bertemu kembali di bawah pohon ketapang di batas desa, tepat ketika purnama ke-36 tiba.
Namun sejarah, seperti yang sering kita tahu, jarang berpihak pada mereka yang jujur. Saat Saija kembali dengan rindu yang tak sempat menua, ia hanya menemukan kehampaan. Adinda dan keluarganya telah melarikan diri ke Lampung untuk menghindari penindasan yang semakin mencekik, hanya untuk menemui ajal secara tragis di ujung bayonet serdadu kolonial. Membayangkan Saija berdiri seorang diri di bawah pohon ketapang itu, menunggu janji yang tak pernah datang hingga meninggalkan luka yang mendalam.
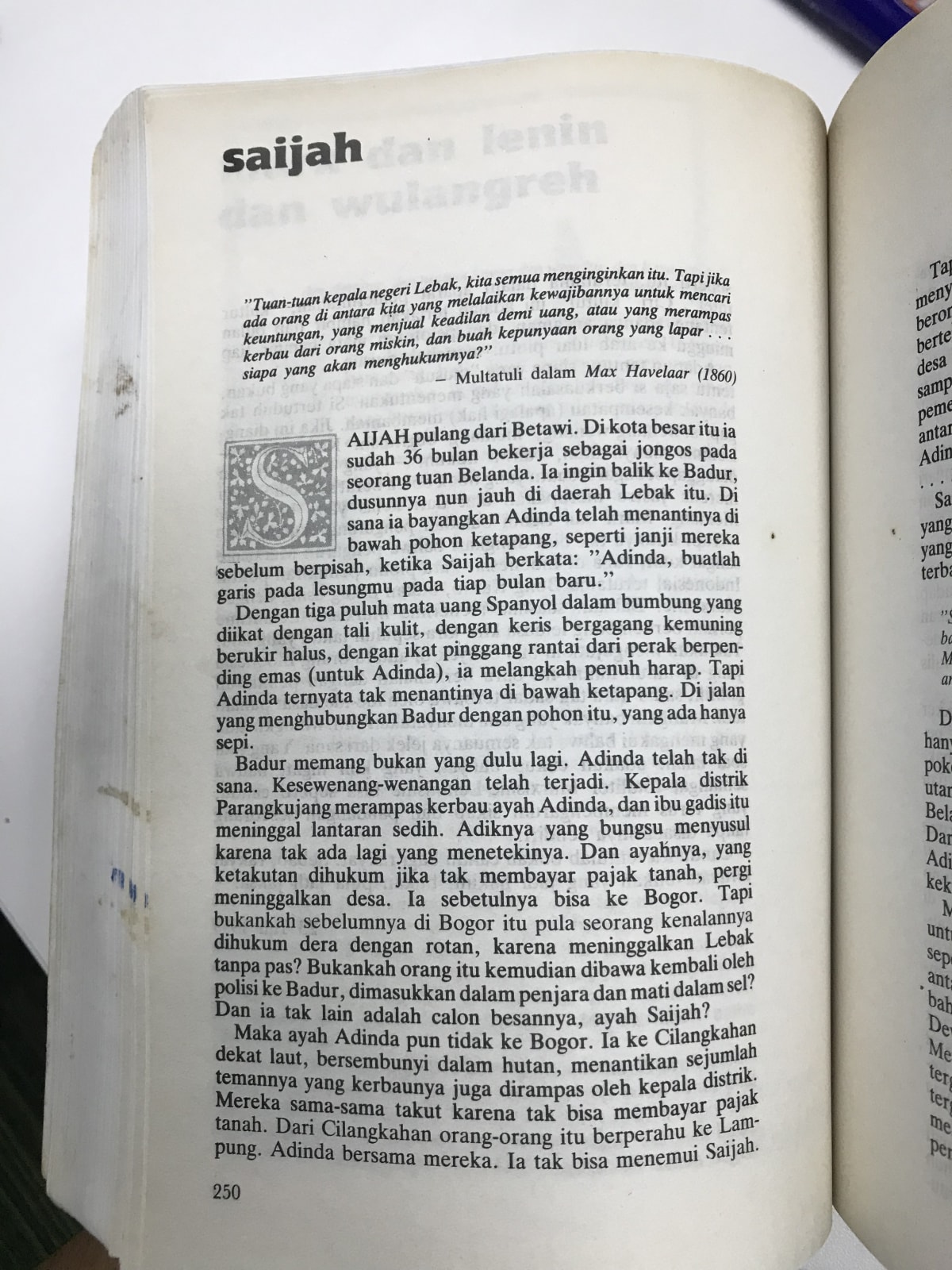
Representasi Penantian yang Getir
Hasrat untuk menelusuri kisah ini semakin menguat secara tak terduga lewat musik. Dalam sebuah penampilan The Trees and The Wild, lagu berjudul “Saija” terasa seperti napas baru bagi tragedi lama itu. Liriknya singkat, nyaris tanpa hiasan, namun menghantam dengan sunyi yang telak:
"Saija remuk / Dan dia 'kan sadar / Yang tak diam dengannya / Hanya waktu."
Secara musikal, lagu ini menyerupai penantian itu sendiri. Ia dimulai dengan petikan gitar yang minimal, seperti kesunyian Desa Badur, lalu perlahan menggema menjadi gelombang post-rock yang megah, seolah meniru harapan Saija yang tumbuh, sebelum akhirnya hancur di bawah kejamnya kolonialisme.

Ziarah ke Rumah Sang Penulis
Dari sanalah keputusan itu diambil. Saya berangkat ke Rangkasbitung. Kota ini, yang selama ini hanya saya kenal sebagai pemberhentian akhir KRL, mendadak menjelma sebagai panggung sejarah yang hidup. Ada dua tempat yang memberi saya cara pandang yang berbeda.
Museum Multatuli: Setibanya di sana, saya disambut oleh representasi visual Multatuli, Adinda, dan Saija dalam rupa patung perunggu. Deretan edisi lama Max Havelaar tersusun rapi di balik kaca, membuat sejarah terasa tidak lagi jauh atau abstrak. Di salah satu dinding, terpampang kalimat yang menjadi inti dari seluruh perjalanan ini:“Tugas manusia adalah menjadi manusia.”



Rumah Dinas Multatuli: Saya juga mengunjungi bekas Rumah Dinas Multatuli (Residentie Assisten Resident Van Lebak), tempat Eduard Douwes Dekker pernah tinggal sebagai Asisten Residen Lebak. Bangunannya kini tampak tidak terawat, dengan tanda Cagar Budaya di depannya. Namun di sanalah ia menyaksikan langsung kesewenang-wenangan yang kelak ia tuliskan menjadi protes moral yang mengguncang dunia. Berdiri di tanah itu, melihat arsip-arsip tua dan buku-buku lama, saya merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan.

Ketika melangkah keluar dari Museum Multatuli, saya menatap langit Rangkasbitung dengan kesadaran yang bertambah. Perjalanan yang bermula dari selembar esai, berlanjut dalam lagu tentang waktu dan kehancuran, kini mewujud dalam langkah kaki yang nyata. Saija memang tokoh rekaan, tetapi penderitaan dan harapan yang ia wakili adalah bagian dari napas sejarah kita. Dan mungkin, juga dari napas kita hari ini.
Rangkasbitung - 21 Mei 2023
